
Bus, Ambulans, dan Nostalgia Dunia Abadi

“Bukankah hidup itu adalah kebahagiaan yang tidak sempurna—perhatian dan kelelahan, kelelahan dan perhatian, dengan harapan kosong, kepalsuan aneh dari hari esok yang lebih cerah? Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengasuh anak nakal dengan senang hati, menenangkan sampai dia tertidur pulas, dan setelah itu kita bisa meninggalkan dia.”
Nostalgia dunia abadi
Dari ungkapan pengalaman religius itu terlihat kehalusan, kepasrahan, dan keinginan untuk terus-menerus menghadirkan dimensi yang sakral (‘bukankah hidup itu adalah kebahagiaan yang tidak sempurna?’) dengan dimensi yang profan, sederhana, sepele dan sangat bersifat keseharian (‘mengasuh anak nakal dengan senang hati sampai dia tertidur pulas’).
Persoalan pengalaman religius yang menyiratkan kerinduan akan dunia yang sakral kemudian mendapat elaborasinya lebih jauh di tangan Mircea Eliade, seorang sejarawan agama-agama yang hidup pada pertengahan abad 20.
Pada 1968, ketika ia menjelaskan ruang yang sakral dalam dimensi agama—yang mana sering direpresentasikan dalam bentuk tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, atau bahkan hutan dan tempat keramat bagi para penghayat kepercayaan lokal—kerinduan akan dunia yang sakral itu bahkan mengalir lebih deras dibanding pengalaman religius yang terjadi di tingkat personal.
Simbol-simbol di dalam tempat suci sekaligus aneka ritus yang kerap dilakukan di dalamnya, merujuk pendapat Eliade, dengan demikian berfungsi sebagai perantara bagi seorang manusia untuk senantiasa berhubungan dengan sesuatu yang transenden dan suci.
Hal itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan, akibat dari buah kerinduan yang muncul di tataran personal sebelumnya. Sehingga, yang terjadi kemudian pada diri seorang yang “religius”—selebar apapun definisi kata itu—adalah semacam nostalgia akan dunia yang abadi.
“Seseorang yang religius menemukan nostalgia di dalam keinginannya untuk mencapai ‘dunia yang abadi’,” terang Eliade.
“Hasrat untuk membuat rumah atau wilayahnya tempat berpijak sebagai tempat para dewa, yang mana pada perjalannya kemudian kerap direpresentasikan dalam bentuk kuil-kuil dan santuari. Pendeknya, nostalgia religius ini mengungkapkan hasrat untuk hidup dalam tataran alam semesta yang murni dan suci, yang seakan-akan baru tercipta pertama kali,” tuturnya di dalam karyanya yang terkenal, The Sacred and The Profane (1968).
Adanya berbagai pengalaman “yang sakral” dan “yang profan” dalam pengalaman religius itu sudah sepantasnya mendapatkan kembali napasnya kini.
Hari ini, kata ‘agama’ kerap kali terdengar sebagai sesuatu yang “adiluhung”, sehingga setiap penafsiran baru atasnya kerap dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan memicu kontroversi yang berlebihan, lantas berujung polemik serta konflik.
Atau sebaliknya, pada hari ini kata ‘agama’ dimaknai sebagai sesuatu yang kerap mencemaskan, dan menjadi justifikasi untuk menebar kebencian serta menghakimi kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas yang berbeda.
Meski ujaran itu tidak lagi baru pada 2016 ini, upaya untuk menghadirkan wajah agama yang bermula dari spiritualitas yang welas asih dan senantiasa menebar kebaikan pada sesama, sepertinya tidak akan pernah aus dari zaman ke zaman.
Bagi mereka yang kerap cemas, tertekan, atau bahkan menderita oleh ancaman plus tendensi perilaku keagamaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman di ruang publik maupun privat, kehadiran spiritualitas yang menekankan welas asih dan toleran pada siapa saja tanpa memandang negatif identitas seorang individu, merupakan sesuatu yang kerap dirindukan.
Sesuatu yang dirindukan layaknya oase bagi para pejalan jauh yang telah lelah mengembara dari hari ke hari di bawah terpaan sinar matahari yang benderang.
Jumlah para pejalan, pengembara yang senantiasa mencari oase itu barangkali kecil dalam statistik.
Namun, lewat berbagai contoh dan ujaran pengalaman religius yang merindukan “dunia yang abadi” di kolong langit yang profan, bukankah kita semua juga telah mengetahui, bahwa hidup ini tidak melulu berisi soal angka?
Dari semua contoh dan ujaran itu, bukankah hidup semestinya juga perihal aneka pengalaman yang indah, penuh pesona, dan karenanya memiliki nilai serta makna yang abadi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.






















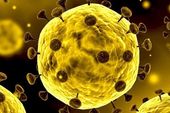


![[HOAKS] Hacker asal Aljazair Dihukum Mati karena Bantu Palestina](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)




































