Bus, Ambulans, dan Nostalgia Dunia Abadi
Kerumunan terlihat jelas di sebuah jalan kecil di samping terminal. Garis polisi belum terlihat. Namun, kejadian itu tampaknya membuat suasana cukup ramai.
Sang kondektur tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin, bagi dia dan banyak orang, kejadian itu biasa saja. Sama seperti banyak kejadian yang berlalu dalam hidupnya.
Tidak ada istimewa. Pun termasuk kejadian satu orang yang kehilangan harapan, lantas memilih gantung diri pada suatu sore di ruko di dekat terminal.
Kenapa orang bisa kehilangan harapan?
Kalau mencermati sejarah agama-agama, jamak diketahui pada mulanya agama menjadi sahabat bagi siapa saja yang kehilangan harapan dan menderita.
Tidak perlu banyak diceritakan, tentu, tentang bagaimana para nabi, santo, atau para punggawa agama lainnya kerap bersahabat dengan orang-orang yang lemah dan papa.
Bagi orang-orang yang lemah dan papa, agama memang kerap kali menawarkan harapan untuk tidak berputus asa.
Kekuatan harapan itulah yang agaknya sering dijadikan landasan untuk terus menjalani hari demi hari dengan batin yang tenang, meski tentu saja esok hari masih misteri. Apa duka atau suka yang akan datang menghampiri?
Cerita ironis dalam kisah kematian
Bicara tentang agama dan harapan, omong-omong, selalu mengingatkan pada cerita seorang kawan. Ia mempunyai seorang adik laki-laki.
Sebut saja nama adik laki-laki itu Hanry. Ia, bersama kakak dan keluarganya, tinggal dan besar di kampung di tanah Batak yang jauh dari keramaian kota.
Pada mulanya Hanry tergolong remaja yang sehat. Namun, tanpa diduga, suatu hari nyamuk Aedes aegypti dengan nakal mengigitnya entah di mana dan kapan.
Akibatnya jelas, ia kena penyakit demam berdarah dan harus berbaring tanpa daya di dipan berhari-hari lamanya.
Keluarga Hanry, memang hanya orang biasa. Untuk pengobatan sehari-hari tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Kompetensi dokter di kampung tidak memadai. Apalagi klinik kecil yang terletak di dekat balai desa.
Kondisi Hanry semakin hari semakin memburuk. Cemas dan sedikit panik, orangtua Hanry memutuskan ingin membawa anaknya ke rumah sakit di kota.
Namun, dari mana biaya ambulans bisa ditanggung?
Kota tempat rumah sakit berada cukup jauh. Belum lagi akses transportasi yang sulit dan buruk di kampung. Biaya ambulans yang sebenarnya tidak seberapa jika diukur dengan penghasilan orang kota, mendadak menjadi kebutuhan yang mendesak, mahal, dan mewah.
Tidak menyerah, orangtua Hanry kemudian berinisiatif meminjam uang dari pintu ke pintu. Mereka berusaha mencari dana pinjaman dari siapa saja yang sekiranya bisa dimintai pertolongan sementara. Namun, inisiatif itu harus dibayar mahal.
Kondisi Hanry terus melemah. Hingga akhirnya, di suatu hari yang tenang, Hanry pun harus menyerah pada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Itu terjadi, ironisnya, justru saat ambulans sudah datang dan ia sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Cerita Hanry yang pergi selamanya dalam mobil ambulans mungkin terdengar klise. Terlebih lagi bagi yang sering mendengar berita tentang konflik dan perang yang berkecamuk.
Satu kematian orang tercinta di dalam sebuah keluarga sederhana, apa boleh buat, kerap kali terlupakan begitu saja dan kurang mempunyai signifikasi yang mendalam.
Bagi Hanry dan keluarga—yang telah berusaha melawan penyakit sekuat tenaga dan meminjam dana ke sana ke mari—kematian itu tentu bermakna lain.
Bagi yang menyaksikan langsung atau berperasaan halus serta kritis, satu pertanyaan barangkali bisa langsung terbersit dalam benak, "Apa arti harapan seperti yang dilontarkan banyak orang, jika pada akhirnya itu semua harus dibabat oleh yang namanya takdir dan kematian?"
Mau tidak mau, berhadapan dengan sesuatu yang abstrak dan sukar dimengerti, manusia kerap menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan, setiap pengalaman yang berasal dari kondisi demikian, sudah tentu, secara langsung atau tidak, bersifat religius.
Pengalaman religius personal
Dalam salah satu sesi kuliahnya yang terjadi pada 1901, William James, filsuf pragmatis yang memiliki latar belakang psikologi cukup kental, menjelaskan dengan gamblang perihal pengalaman-pengalaman religius yang terjadi di tingkat personal.
Tanpa harus terjebak dalam salah satu ajaran agama tertentu, ia menengahkan pengalaman religius ketika berhadapan dengan sesuatu yang transenden, yang akhirnya sering membuat batin manusia diliputi perasaan pasrah, tenang, damai, halus, atau bahkan melankoli indah.
“Pasti ada sisi-sisi khidmat, serius, dan lembut dari semua sikap yang kita sebut beragama. Kita menyebutnya bahagia, namun bukan seringai atau gelak tawa. Kita menyebutnya kesedihan, bukan jeritan atau kutukan,” ujarnya dalam sesi kuliah yang akhirnya dirangkum dalam sebuah karya klasik, The Varieties of Religious Experience (1902:48).
Pengalaman-pengalaman religius yang dialami seseorang, sudah tentu, otentik dan memiliki perangai yang berbeda satu sama lain. Ibarat jatuh cinta pertama kali saat remaja, pengalaman itu memiliki makna khasnya masing-masing yang tidak dapat ditukar dengan seribu keping emas.
Senada dengan itu, ada satu ungkapan yang cukup terkenal tentang perasaan religius yang kerap mengemuka ketika berhadapan dengan sesuatu yang transenden ketika menjalani laku ritual agama.
Rudolf Otto—teolog sekaligus sejarawan agama-agama, pada permulaan abad 20—menyatakan, di setiap pengalaman religius yang dialami oleh para punggawa agama—nabi, santo, pendeta, ulama, biksu—maupun orang-orang biasa, terdapat perasaan “mysterium tremendum et fascinans”.
Ungkapan perasaan itu mengandung pengertian kualitatif dalam memandang pengalaman ketika bersentuhan dengan sesuatu yang transenden, di mana ada aspek gentar, takut, akan kehadiran sesuatu yang asing (mysterium tremendum), sekaligus terasa unik, menarik, dan karenanya penuh pesona (fascinans).
Pengalaman religius tersebut sukar diungkapkan dengan kata-kata, karena berada di balik kemampuan ekspresi yang wajar dilakukan dalam keseharian.
Kata-kata, dalam momen mysterium tremendum et fascinans, menjadi tidak berarti. Sebab, pengalaman langsung telah mengambil alih kesadaran manusia akan ekspresi verbal.
Dalam momen tersebut, yang tersisa barangkali hanyalah keindahan dan kerinduan untuk lepas dari jeratan segala hal yang profan (fana), agar bisa terus-menerus bersentuhan dengan dimensi yang sakral (abadi)—meski tahu, sebagaimana aneka pengalaman religius yang orang-orang sering tunjukkan, semua hal yang “menggetarkan-tapi-indah” itu hanya terjadi sesaat, sementara, dan akan segera musnah.
“Aku bertanya kepadamu, apakah arti hidup manusia?” ungkap William James (1902:50) tentang pengalaman religius yang dialami Frederick Locker Lampson, penyair abad 19 yang sakit-sakitan.
“Bukankah hidup itu adalah kebahagiaan yang tidak sempurna—perhatian dan kelelahan, kelelahan dan perhatian, dengan harapan kosong, kepalsuan aneh dari hari esok yang lebih cerah? Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengasuh anak nakal dengan senang hati, menenangkan sampai dia tertidur pulas, dan setelah itu kita bisa meninggalkan dia.”
Nostalgia dunia abadi
Dari ungkapan pengalaman religius itu terlihat kehalusan, kepasrahan, dan keinginan untuk terus-menerus menghadirkan dimensi yang sakral (‘bukankah hidup itu adalah kebahagiaan yang tidak sempurna?’) dengan dimensi yang profan, sederhana, sepele dan sangat bersifat keseharian (‘mengasuh anak nakal dengan senang hati sampai dia tertidur pulas’).
Persoalan pengalaman religius yang menyiratkan kerinduan akan dunia yang sakral kemudian mendapat elaborasinya lebih jauh di tangan Mircea Eliade, seorang sejarawan agama-agama yang hidup pada pertengahan abad 20.
Simbol-simbol di dalam tempat suci sekaligus aneka ritus yang kerap dilakukan di dalamnya, merujuk pendapat Eliade, dengan demikian berfungsi sebagai perantara bagi seorang manusia untuk senantiasa berhubungan dengan sesuatu yang transenden dan suci.
Hal itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan, akibat dari buah kerinduan yang muncul di tataran personal sebelumnya. Sehingga, yang terjadi kemudian pada diri seorang yang “religius”—selebar apapun definisi kata itu—adalah semacam nostalgia akan dunia yang abadi.
“Seseorang yang religius menemukan nostalgia di dalam keinginannya untuk mencapai ‘dunia yang abadi’,” terang Eliade.
“Hasrat untuk membuat rumah atau wilayahnya tempat berpijak sebagai tempat para dewa, yang mana pada perjalannya kemudian kerap direpresentasikan dalam bentuk kuil-kuil dan santuari. Pendeknya, nostalgia religius ini mengungkapkan hasrat untuk hidup dalam tataran alam semesta yang murni dan suci, yang seakan-akan baru tercipta pertama kali,” tuturnya di dalam karyanya yang terkenal, The Sacred and The Profane (1968).
Adanya berbagai pengalaman “yang sakral” dan “yang profan” dalam pengalaman religius itu sudah sepantasnya mendapatkan kembali napasnya kini.
Hari ini, kata ‘agama’ kerap kali terdengar sebagai sesuatu yang “adiluhung”, sehingga setiap penafsiran baru atasnya kerap dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan memicu kontroversi yang berlebihan, lantas berujung polemik serta konflik.
Atau sebaliknya, pada hari ini kata ‘agama’ dimaknai sebagai sesuatu yang kerap mencemaskan, dan menjadi justifikasi untuk menebar kebencian serta menghakimi kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas yang berbeda.
Meski ujaran itu tidak lagi baru pada 2016 ini, upaya untuk menghadirkan wajah agama yang bermula dari spiritualitas yang welas asih dan senantiasa menebar kebaikan pada sesama, sepertinya tidak akan pernah aus dari zaman ke zaman.
Bagi mereka yang kerap cemas, tertekan, atau bahkan menderita oleh ancaman plus tendensi perilaku keagamaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman di ruang publik maupun privat, kehadiran spiritualitas yang menekankan welas asih dan toleran pada siapa saja tanpa memandang negatif identitas seorang individu, merupakan sesuatu yang kerap dirindukan.
Sesuatu yang dirindukan layaknya oase bagi para pejalan jauh yang telah lelah mengembara dari hari ke hari di bawah terpaan sinar matahari yang benderang.
Jumlah para pejalan, pengembara yang senantiasa mencari oase itu barangkali kecil dalam statistik.
Namun, lewat berbagai contoh dan ujaran pengalaman religius yang merindukan “dunia yang abadi” di kolong langit yang profan, bukankah kita semua juga telah mengetahui, bahwa hidup ini tidak melulu berisi soal angka?
Dari semua contoh dan ujaran itu, bukankah hidup semestinya juga perihal aneka pengalaman yang indah, penuh pesona, dan karenanya memiliki nilai serta makna yang abadi?
https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/11274011/bus-ambulans-dan-nostalgia-dunia-abadi









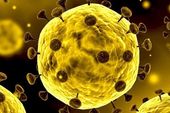

![[HOAKS] Hacker asal Aljazair Dihukum Mati karena Bantu Palestina](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)































