
Bus, Ambulans, dan Nostalgia Dunia Abadi

Kondisi Hanry terus melemah. Hingga akhirnya, di suatu hari yang tenang, Hanry pun harus menyerah pada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Itu terjadi, ironisnya, justru saat ambulans sudah datang dan ia sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Cerita Hanry yang pergi selamanya dalam mobil ambulans mungkin terdengar klise. Terlebih lagi bagi yang sering mendengar berita tentang konflik dan perang yang berkecamuk.
Satu kematian orang tercinta di dalam sebuah keluarga sederhana, apa boleh buat, kerap kali terlupakan begitu saja dan kurang mempunyai signifikasi yang mendalam.
Bagi Hanry dan keluarga—yang telah berusaha melawan penyakit sekuat tenaga dan meminjam dana ke sana ke mari—kematian itu tentu bermakna lain.
Bagi yang menyaksikan langsung atau berperasaan halus serta kritis, satu pertanyaan barangkali bisa langsung terbersit dalam benak, "Apa arti harapan seperti yang dilontarkan banyak orang, jika pada akhirnya itu semua harus dibabat oleh yang namanya takdir dan kematian?"
Dilihat dalam konteks yang lebih luas, cerita Hanry yang mati bisa jadi merupakan ilustrasi penting tentang bagaimana harapan bersangkut paut dengan yang namanya kematian. Kedua hal itu memang sedikit aneh dan kerap menimbulkan perasaan cemas dalam diri.
Mau tidak mau, berhadapan dengan sesuatu yang abstrak dan sukar dimengerti, manusia kerap menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan, setiap pengalaman yang berasal dari kondisi demikian, sudah tentu, secara langsung atau tidak, bersifat religius.
Pengalaman religius personal
Dalam salah satu sesi kuliahnya yang terjadi pada 1901, William James, filsuf pragmatis yang memiliki latar belakang psikologi cukup kental, menjelaskan dengan gamblang perihal pengalaman-pengalaman religius yang terjadi di tingkat personal.
Tanpa harus terjebak dalam salah satu ajaran agama tertentu, ia menengahkan pengalaman religius ketika berhadapan dengan sesuatu yang transenden, yang akhirnya sering membuat batin manusia diliputi perasaan pasrah, tenang, damai, halus, atau bahkan melankoli indah.
“Pasti ada sisi-sisi khidmat, serius, dan lembut dari semua sikap yang kita sebut beragama. Kita menyebutnya bahagia, namun bukan seringai atau gelak tawa. Kita menyebutnya kesedihan, bukan jeritan atau kutukan,” ujarnya dalam sesi kuliah yang akhirnya dirangkum dalam sebuah karya klasik, The Varieties of Religious Experience (1902:48).
Pengalaman-pengalaman religius yang dialami seseorang, sudah tentu, otentik dan memiliki perangai yang berbeda satu sama lain. Ibarat jatuh cinta pertama kali saat remaja, pengalaman itu memiliki makna khasnya masing-masing yang tidak dapat ditukar dengan seribu keping emas.
Senada dengan itu, ada satu ungkapan yang cukup terkenal tentang perasaan religius yang kerap mengemuka ketika berhadapan dengan sesuatu yang transenden ketika menjalani laku ritual agama.
Rudolf Otto—teolog sekaligus sejarawan agama-agama, pada permulaan abad 20—menyatakan, di setiap pengalaman religius yang dialami oleh para punggawa agama—nabi, santo, pendeta, ulama, biksu—maupun orang-orang biasa, terdapat perasaan “mysterium tremendum et fascinans”.
Ungkapan perasaan itu mengandung pengertian kualitatif dalam memandang pengalaman ketika bersentuhan dengan sesuatu yang transenden, di mana ada aspek gentar, takut, akan kehadiran sesuatu yang asing (mysterium tremendum), sekaligus terasa unik, menarik, dan karenanya penuh pesona (fascinans).
Pengalaman religius tersebut sukar diungkapkan dengan kata-kata, karena berada di balik kemampuan ekspresi yang wajar dilakukan dalam keseharian.
Kata-kata, dalam momen mysterium tremendum et fascinans, menjadi tidak berarti. Sebab, pengalaman langsung telah mengambil alih kesadaran manusia akan ekspresi verbal.
Dalam momen tersebut, yang tersisa barangkali hanyalah keindahan dan kerinduan untuk lepas dari jeratan segala hal yang profan (fana), agar bisa terus-menerus bersentuhan dengan dimensi yang sakral (abadi)—meski tahu, sebagaimana aneka pengalaman religius yang orang-orang sering tunjukkan, semua hal yang “menggetarkan-tapi-indah” itu hanya terjadi sesaat, sementara, dan akan segera musnah.
“Aku bertanya kepadamu, apakah arti hidup manusia?” ungkap William James (1902:50) tentang pengalaman religius yang dialami Frederick Locker Lampson, penyair abad 19 yang sakit-sakitan.























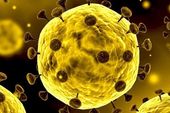

![[HOAKS] Hacker asal Aljazair Dihukum Mati karena Bantu Palestina](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)





































