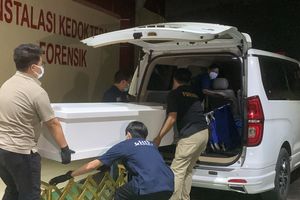Juga, menjadi tak relevan didiskusikan di sini, apakah Pasal 156 dan 156a KUHP tentang penodaan agama benar-benar "pasal karet" yang bisa disalahgunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan untuk kepentingan apa saja.
Ketika akal sehat tidak bekerja, maka hukum menjadi "liar" dan arah pedang keadilan pun akhirnya didasarkan pada tafsir subyektif aparat penegak hukum selaku "wakil Tuhan". Kontroversi vonis majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara atas Ahok saya kira mengonfirmasi hal itu.
(Baca juga: Jokowi Heran Pilkada DKI Selesai, tetapi Suhu Politik Masih Panas)
Kotak pandora
Problemnya bertambah kompleks karena Ahok adalah seorang sosok gubernur petahana yang tak sekadar keras, temperamental, dan tak kenal kompromi dalam menindak koruptor, tetapi juga seorang figur yang memikul beban minoritas ganda, yakni sebagai pemeluk Kristiani sekaligus Tionghoa. Akibatnya, persaingan para calon dalam Pilkada DKI tak hanya membuka kotak pandora isu-isu primordial berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan klasik esensi keindonesiaan kita, termasuk isu sensitif, relasi agama dan politik (negara).
Reli-reli aksi massa dengan label "bela Islam" di satu pihak, dan "bela NKRI" serta kebinekaan di lain pihak, baik sebelum maupun pasca-Pilkada DKI, adalah refleksi terbukanya kotak pandora yang membahayakan dan tak diinginkan itu. Betapa tidak, tak pernah terjadi sebelumnya tingkat saling curiga dan saling tak percaya di antara berbagai elemen bangsa kita begitu mengkhawatirkan seperti dirasakan hari-hari ini. Tak mengherankan jika Presiden Jokowi merasa perlu bertemu banyak tokoh masyarakat dalam banyak kesempatan dengan pesan berulang-ulang yang sangat jelas, yakni agar kita semua berdiri tegak di atas konstitusi dan kembali kepada cita-cita Republik yang diproklamasikan pada 1945.
Ajakan Presiden untuk kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni negara kesatuan berbentuk republik yang berfondasikan keberagaman dengan falsafah dasar Pancasila, tentu sangat beralasan dan karena itu patut diapresiasi. Terlalu mahal taruhan bagi bangsa ini jika keterbelahan politik dan sosial bermuara pada konflik sektarian yang bisa mencabik-cabik negeri ini seperti dialami sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa Timur. Meski demikian, mewujudkan harapan Presiden Jokowi dalam jangka pendek bukanlah pekerjaan mudah. Persoalannya, suasana saling curiga dan politik yang keruh memiliki akar masalah yang kompleks. Bagaimanapun suasana bangsa kita hari ini adalah produk dari akumulasi kelalaian yang sudah bertumpuk sejak puluhan tahun yang lalu. Ada beberapa faktor yang bisa dicermati.
Ambivalensi negara
Pertama, ambivalensi negara dalam menyikapi bangkitnya gerakan-gerakan radikal agama, dan juga tumbuhnya berbagai aliran "sempalan" agama, sehingga yang tampak secara publik adalah tak adanya konsistensi negara dalam penegakan hukum. Terkait maraknya aliran agama, misalnya, di satu pihak negara diamanatkan konstitusi melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara, termasuk kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Namun, di pihak lain negara dan institusi representasi negara, seperti pemda, kodim, polres, polsek, koramil, dan seterusnya, cenderung membiarkan dan bahkan acap kali memfasilitasi penindasan dan represi suatu kelompok masyarakat atas kelompok lain.
Itulah misalnya yang dialami jemaah Ahmadiyah di sejumlah daerah serta jemaah Syiah di Sampang, Madura. Mereka, warga negara yang memiliki hak dilindungi negara, terusir dan diusir dari kampung halaman oleh saudara sebangsa sendiri hanya karena berbeda aliran dan/atau keyakinan dalam beragama. Selain sikap mendua negara, tampak pula tak ada konsistensi negara dalam penegakan supremasi hukum. Tumbuh suburnya kelompok-kelompok radikal dan anti-Pancasila pada dasarnya produk dari inkonsistensi itu.
Kedua, kegagalan pemerintah-pemerintah sejak Indonesia merdeka mengelola keindonesiaan yang berbasiskan keberagaman. Hampir tidak ada keseriusan memperkuat fondasi kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika berhenti sebagai semboyan belaka. Selama lebih dari 70 tahun merdeka tak pernah ada upaya serius bagaimana keberagaman secara agama, ras, etnik, dan daerah dikonversi, dikelola, dan dikapitalisasi sebagai aset dalam mewujudkan Indonesia yang kokoh, adil, makmur, dan sejahtera.
Sejak dahulu pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan negara. Fokus yang tak pernah berhenti untuk mengejar pertumbuhan ekonomi merefleksikan hal itu. Kurang menjadi perhatian bahwa dampak orientasi berlebihan pada pertumbuhan ekonomi adalah semakin tajam dan melebarnya ketimpangan sosial. Tak mengherankan jika segelintir orang Indonesia menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional. Problem bertambah rumit ketika mayoritas mereka yang menguasai ekonomi itu berasal dari kelompok minoritas, baik agama maupun etnik.
Ketiga, meskipun era reformasi telah berlangsung hampir dua dekade, sulit dimungkiri bahwa bangsa kita hingga hari ini tidak pernah bisa benar-benar "hijrah" dan menarik garis batas yang jelas dari rezim otoriter Orde Baru. Cara pandang Orde Baru yang cenderung melembagakan suasana saling tak percaya di antara berbagai elemen bangsa terus direproduksi dan dipelihara, bukan oleh negara, melainkan oleh para operator profesional yang bersekongkol dengan para pebisnis hitam, politisi busuk, dan para radikalis agama. Hal ini tampak dari upaya mempertentangkan pribumi dan nonpribumi, peruncingan sentimen berbasis SARA, khususnya antara yang Muslim dan "kafir", begitupun penciptaan fobia terhadap bahaya "kebangkitan" PKI dan komunisme, yang semuanya adalah replika otentik dari politik rezim Soeharto.
Tidak mustahil para operator pemelihara konflik memanfaatkan durian runtuh kasus Ahok bukan sekadar untuk mengganjal Ahok, melainkan juga dalam rangka menghentikan mentor politik Ahok, yakni Presiden Jokowi, sekurang-kurangnya agar hanya berkuasa hingga 2019. Sangat bisa diduga tak sedikit pemilik gurita bisnis besar yang terganggu kenyamanannya akibat kebijakan Jokowi dan Ahok yang merugikan mereka sehingga mereka terus memelihara politik yang keruh dalam suasana saling curiga yang mencemaskan kita semua.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Jokowi kecuali tetap berdiri tegas lurus di atas konstitusi untuk menegakkan cita-cita para pendiri Republik, yakni sebuah Indonesia yang berbasis keberagaman sebagaimana terkristalisasi di dalam falsafah dasar negara Pancasila. Juga, tidak ada pilihan lain bagi elemen masyarakat sipil kecuali memelihara akal sehat dan kewarasan agar tidak turut terperosok tipu daya para pebisnis hitam, politisi busuk, dan kaum radikalis agama.
SYAMSUDDIN HARIS,
Profesor Riset LIPI
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Juni 2017, di halaman 6 dengan judul "Mengapa Politik Keruh".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.