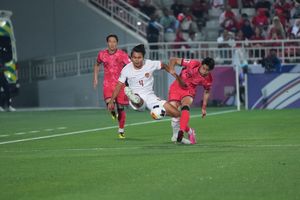Memerintah Bersama Rakyat

Jika kita mengikuti pemberitaan selama setahun terakhir, jujur kita akui bahwa konsolidasi politik dan rivalitas elite di seputar lingkar kekuasaan adalah tantangan yang tak mudah di masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK. Padahal konsolidasi politik sangat dibutuhkan oleh setiap pemerintahan untuk menjalankan agenda-agenda pembangunannya secara efektif.
Tarik-tarik menarik antar berbagai kekuatan politik yang dominan ini diduga telah melatarbelakangi sejumlah insiden politik dan kebijakan kontroversial yang pada gilirannya mendapat resistensi publik.
Paling tidak itu kita rasakan dan saksikan dalam sejumlah kasus heboh mulai dari penunjukan Kapolri tahun lalu, drama pergantian Ketua DPR, revisi UU KPK, sampai pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang hangat.
Termasuk juga drama panjang perpecahan dua partai besar, Partai Golkar dan PPP. Dan, tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan kemunculan fenomena Gafatar, serangan dan ancaman teroris ISIS, serta isu LGBT!
Sebagai pemerintahan yang berdiri di atas koalisi sejumlah partai dan aktor-aktor ekonomi-politik yang berbeda yang menjadi pendukung pada pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi sesungguhnya sudah cukup cakap dan bijak mengelola dinamika politik yang terjadi sekaligus berupaya mendisiplinkan ordo politik yang dipimpinnya.
Tinggal yang harus diperkuat adalah pengelolaan dinamika politik yang lebih berbobot dan demokratis dalam bingkai pengantisipasian krisis atau merujuk pada penelitian Boin, Hart, Stern dan Sundelius (2005) sebuah the politics of crisis management.
Dari hasil penelitian kolaborasi tiga kampus ini disimpulkan betapa, pertama, positioning kepemimpinan dalam proses pengambilan kebijakan serta, kedua, strategi komunikasi dan argumentasi publik yang sistematik (di situ disebut sebagai meaning making process) menjadi sangat vital dalam menghadapi berbagai ketidakpastian dan tekanan ekonomi politik yang mungkin atau pasti terjadi.
Dalam konteks pilihan-pilihan performa dan respon kepemimpinan serta strategi kebijakan dan komunikasi publik yang sistematik inilah saya hendak memberikan sedikit komentar.
Bagi saya, setting panggung politik yang gaduh pada tataran elite telah membuat gairah (passion) dan makna ‘politik’ menjauh dari esensi dan topik kerakyatan yang justru semestinya harus selalu dijadikan fondasi sekaligus mantra utama pemerintahan Jokowi-JK.
Tentu kita ingat betapa diskursus terpenting milik Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu adalah revolusi mental, poros maritim dan nawa cita. Bukankah melalui diskursus-diskursus inilah diferensiasi platform perubahan Jokowi-JK dapat mencuri perhatian, memberi harapan dan mampu memobilisasi dukungan rakyat?
Alih-alih diperkuat dan direproduksi secara terus-menerus dalam sebuah strategi meaning making process untuk menghadapi ketidakpastian dan tekanan ekonomi-politik seperti yang saat ini terjadi, kita saksikan betapa argumentasi-argumentasi populisme tersebut malah cenderung ditinggalkan.
Harus disadari oleh seluruh aparat pemerintahan Jokowi-JK bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu merupakan sebuah ‘populist reason’, yakni keberhasilan mengkapitalisasi pergulatan panjang politik ‘kebangkitan’ rakyat yang menginginkan perubahan atas nasib dan kehidupan mereka. Disitulah sesungguhnya makna, energi dan kekuatan otentik dari pemerintahan Jokowi yang mesti dijaga keberlanjutan dan realisasinya.
Dalam konteks membangun citra dan argumentasi publik yang populis dan demokratis ini, politik membutuhkan sebuah ‘imajinasi sosiologis’ yang lebih luas dan kreatif. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memahami realitas sosial-politik-ekonomi yang tengah terjadi dan pengaruhnya atas kehidupan mereka. Namun juga imajinasi dibutuhkan agar rakyat bisa mendapatkan opsi-opsi dan jalan keluar dari berbagai kebuntuan yang harus mereka hadapi.
Kebuntuan akibat rivalitas elite dan pertarungan oligarki, kebingungan strategi kebijakan dan komunikasi publik yang terlihat inkonsisten dengan tema-tema kerakyatan, serta di sisi lain upaya presiden untuk melakukan konsolidasi politik kepemimpinannya, harus diimbangi oleh upaya konsolidasi pada tingkat masyarakat sipil.
Imajinasi-imajinasi yang berbuah ide dan aksi yang kreatif oleh aktor-aktor masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk tetap dirawat dan dikembangkan agar Indonesia selamat dari ancaman stagnasi.



















![[KLARIFIKASI] Konteks Keliru, Video Jokowi Mengancam Rakyat](https://asset.kompas.com/crops/eBO9IDEfZo1J1Gruyx_ZjNxQ4cs=/0x0:900x600/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9cb1658efd.jpg)

![[VIDEO] Benarkah Situasi AS Mencekam karena Pemerintahnya Dukung Israel?](https://asset.kompas.com/crops/G-SiEa47BOlg9vsm9Ld085Bza5Y=/128x10:1247x756/170x113/data/photo/2024/03/28/6605892af0750.png)



![[HOAKS] Situasi Amerika Serikat Mencekam karena Pemerintahnya Dukung Israel](https://asset.kompas.com/crops/_w-9Tk8Le5AJkzwJUPH40Mre34Y=/0x0:900x600/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9c94a9f7d9.jpg)