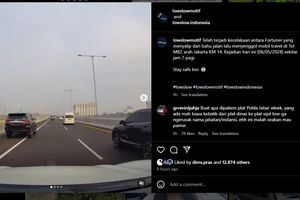ADA pertanyaan ‘nakal’, apakah dengan sistem pemilihan presiden (pilpres) yang ada saat ini, mungkinkah dari kalangan minoritas, terutama suku di luar Pulau Jawa atau bukan orang Jawa jadi presiden di Indonesia?
Secara konstitusi mungkin saja. Karena dalam Pasal 6A UUD 1945, disebutkan syarat presiden antara lain, adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Namun dalam realitas politik akan sulit diwujudkan. Mengapa? karena sistem pilpres di Indonesia belum memungkinkan, cenderung menipiskan peluang itu.
Dengan menggunakan sistem suara terbanyak (popular vote) dalam pilpres, akan ada kecenderungan menguatnya politik identitas untuk meraup suara dari ceruk pemilih dengan latar identitas yang sama, terutama dari kelompok mayoritas.
Sistem pilpres yang bersandar pada popular vote, memungkinkan ‘mayoritas’ selalu tampil sebagai pemenang. Apalagi bila kemudian latar identitas calon presiden dikelola untuk menggiring dan meraup sentimen pemilih.
Baca juga: Mempersempit Peluang Politisi Kaget dan Caleg Pansos
Dalam kultur masyarakat dengan kecenderungan politik identitas masih kuat, etnik atau sub etnik dengan populasi relatif sedikit memiliki peluang yang tipis, bila tak mau dikatakan tidak ada, untuk terpilih atau dipilih sebagai kepala negara.
Dengan politik identitas, akan selalu tampil ‘tirani’ mayoritas. Oleh kelompok kepentingan, demi meraih kekuasaan, identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem, dengan tujuan mendapat dukungan politik.
Insentif elektoral lewat politik identitas biasanya ingin didapat oleh kontestan politik dari orang-orang yang merasa atau mengidentifikasi diri 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Misalnya, paradigma formulasi atau konfigurasi pasangan ‘Jawa-luar Jawa’ dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, sejatinya sedari awal telah memperlihatkan adanya logika fallacy dan bias politik identitas.
Tentu saja, karena dalam logika dan hitungan politik semacam itu, ceruk politik mayoritas secara etnik atau suku sudah diletakan di awal sebagai faktor determinan mendorong kandidasi ketimbang kapasitas, integritas dan jejak rekam kandidat kepala negara.
Dalam logika dan kalkulasi politik yang menempatkan keunggulan latar identitas dalam segi jumlah populasi, menjadikan minoritas secara identitas (suku, agama dan ras) dengan sendirinya harus menurunkan harapan menjadi orang nomor satu di republik ini.
Selain politik identitas, ketidakadilan distributif dan struktural, yang berdampak pada distribusi kualitas penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak merata di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa, makin memperkecil peluang untuk turut dalam kandidasi.
Tidak mudah bagi generasi bangsa dari daerah-daerah dengan mutu penyelenggaraan pendidikan yang rendah untuk bersaing secara terbuka dalam berbagai bidang, di semua level, dengan mereka yang berasal dari daerah yang lebih maju pendidikannya.
Ketidakadilan distributif dalam pendidikan bisa dilihat dari rilis Webometrics. Lembaga yang rutin melakukan pemeringkatan universitas-universitas terbaik di dunia itu, tahun 2023 ini mengkonfirmasi bahwa dari 10 universitas terbaik di Indonesia, sembilan di antaranya ada di Pulau Jawa.
Dengan disparitas atau ketimpangannya begitu menonjol, dari luar Jawa jangankan untuk bisa menjadi presiden yang dipilih oleh jutaan orang (kalah jumlah populasi), untuk menjadi menteri saja sulit. Kalau pun bisa, hampir dipastikan itu lebih karena pertimbangan politik atau kedekatan personal, bukan pada merit sistem.
Bisa dilihat, komposisi dari kabinet ke kabinet, semua rezim pemerintahan, terutama di era reformasi, didominasi dari Pulau Jawa.
Dalam kabinet Presiden Jokowi periode kedua ini, misalnya, dari 34 menteri, 28 orang di antaranya berasal dari satu suku, yaitu Jawa.
Lumrah bila kemudian, orang Maluku merasa kecewa, karena sudah 45 tahun, tidak ada figur mereka diberi kesempatan menjadi menteri. Terakhir G.A. Siwabessy, Menteri Kesehatan tahun 1978. Padahal sejak periode awal kemerdekaan, orang Maluku selalu ada dalam komposisi kabinet.
Realitas politik semacam ini, menyebabkan keadilan menjadi kontradiktif, karena tak disertai distribusi kekuasaan yang merata (no distribution of justice without distribution of power).
Sementara pada titik yang sama, demokrasi elektoral melalui pilpres yang bertumpu pada popular vote dan one man one vote pun bergantung pada kualitas para pemilih, yang tentu saja terbentuk melalui pendidikan yang berkualitas.
Memberikan sinyalemen yang kuat kepada kita, bahwa mestinya atau saatnya sirkulasi elite, melalui sistem pilpres yang dianut sekarang ini harus ditinjau atau ditata ulang. Sembari distribusi atau penyelenggaraan pendidikan dibuat lebih adil dan merata.
Soal ini tentu kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan di Amerika Serikat, dalam memilih sistem pilpres, seperti yang saya tulis sebelumnya di kolom ini “Sistem Pilpres ‘Diskriminatif’ Melanggengkan Ketimpangan” (Kompas.com, 26/05/2023).
Negara besar yang dihuni berbagai etnik, dengan proporsi sebaran populasi tidak sama pada setiap negara bagian, juga turut memikirkan dan mengantisipasi situasi politik yang mungkin terjadi.
Saat merumuskan sistem pilpres di Amerika Serikat, Konvensi Konstitusi negara itu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kecenderungan politik identitas yang bakal mengemuka, untuk kemudian diantisipasi.
Keraguan terhadap kapasitas pemilih serta ketakutan bahwa tanpa pengetahuan yang memadai terkait para kandidat, pemilih akan cenderung memilih kandidat yang punya kesamaan ‘identitas’ atau berasal dari negara bagian mereka sendiri, turut dipertimbangan.
Selain itu, dipertimbangkan pula kekhawatiran pilpres dengan sistem popular vote akan membuat negara bagian berpenduduk banyak lebih mendominasi pemerintahan dan kemudian mengesampingkan negara-negara bagian yang berpenduduk sedikit.
Sehingga untuk mengantisipasinya, Amerika Serikat kemudian menetapkan sistem yang lebih adil dan dapat mengakomodasi kepentingan negara bagian yang sedikit jumlah populasi.
Itu pula mengapa mekanisme pemilihan dengan suara terbanyak atau popular vote tidak menjadi pilihan dalam pilpres di Amerika Serikat, meski keinginan itu sempat mengemuka dalam Konvensi Konstitusi.
Baca juga: Antara Korupsi Politik dan Politisasi Korupsi
Justru yang dipilih adalah sistem electoral college. Satu sistem yang menghendaki capres harus menang di lebih banyak negara bagian, yang besar maupun sedikit populasi. Seperti lomba banyak-banyakan menang di negara bagian, begitu kira-kira.
Sebuah sistem yang dalam praktiknya memang terlihat lebih rumit, namun dapat menjadikan semua negara bagian dan termasuk warganya, ada dalam posisi yang sama penting, strategis dan ‘seksi’ secara elektoral.
Dengan sistem itu pula, pada pilpres tahun 2000, kandidat Republikan yang saat itu adalah gubernur Texas George W. Bush mampu menyingkirkan Al Gore kandidat Demokrat yang kala itu masih menjabat wakil presiden.
Dalam pemilu yang sengit itu, kemenangan justru ditentukan oleh Florida, negara bagian yang relatif kecil. Bush akhirnya menang, sekalipun waktu itu kalah dalam popular vote, namun unggul secara electoral college.
Begitupun Barack Obama, bisa menjadi presiden kulit hitam pertama, representasi kalangan minoritas di Amerika, keturunan dari ayah seorang Muslim asal Kenya, dapat mengalahkan McCain pada 2008, juga dimungkinkan karena sistem electoral college.
Atau dalam pilpres 2016 di mana kandidat Republikan Donald J. Trump mampu menjungkal kandidat Demokrat Hillary Clinton. Sekalipun Clinton saat itu unggul 3 juta suara popular vote di atas Trump, namun kalah dalam jumlah electoral college dari Trump.
Walau mendapat suara terbanyak di New York dan California, negara bagian dengan populasi yang banyak atau lebih besar, ternyata Clinton tersingkir dan harus mengakui keunggulan Trump.
Itu karena dalam sistem yang dianut Amerika Serikat, penentu kemenangan seorang capres bukan didasarkan total suara secara nasional, melainkan pada alokasi suara berdasarkan porsi kemenangan di 51 negara bagian.
Kemenangan di setiap negara bagian menentukan kemenangan sang capres, bukan total jumlah suara yang diperoleh oleh para capres.
Dengan sistem ini, suara yang kalah di negara bagian otomatis tidak akan dihitung, sebab berlaku sistem winner-takes-all.
Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem jumlah total suara terbanyak atau popular vote dari semua wilayah dan daerah di Indonesia. Sehingga kandidat presiden cukup menang signifikan di Jawa, sudah otomatis dapat terpilih menjadi presiden.
Sebuah sistem pilpres yang turut melanggengkan atau dapat menyuburkan politik identitas dan membuka ruang yang jauh lebih besar bagi diusungnya capres dari etnik berpopulasi besar (baca: capres Jawa versus Jawa).
Serta meminggirkan peluang bagi kandidat yang berasal dari daerah dengan populasi penduduk atau etnik yang relatif sedikit, seperti yang berasal atau berlatar dari ras Melanesia yang tersebar di kawasan timur Indonesia.
Belum lagi soal syarat 20 persen untuk ambang batas presidential threshold yang juga kian mempersempit peluang ‘orang daerah’. Harapan makin pupus bila kemudian situasi partai politik dikuasai kartel politik serta elite oligarki.
Makin menyusutkan persaingan dan memperkecil ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi atau turut serta, ambil bagian, berkontestasi dalam pilpres.
Keadaan atau realitas politik yang mestinya mendapat perhatian bersama, terutama oleh anggota parlemen di tingkat pusat untuk mencari format atau sistem yang lebih relevan dengan demografi politik dan kondisi eksisting Indonesia.
Upaya ke arah itu tentu saja dimungkinkan, sebab pelaksanaan demokrasi merupakan sebuah proses terus-menerus, yang ditandai oleh perbaikan atau penyempurnaan sistem politik dan pemilu termasuk partai politik.
Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara demokratis yang telah mapan pun, hingga kini masih terus memperbaiki sistem dan aturan mereka, sehingga mampu menjawab realitas atau adaptif dengan tantangan zaman.
Semestinya Indonesia juga demikian. Penyempurnaan sistem politik menjadi agenda penting guna menjaga dan memastikan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dengan belajar dari pengalaman yang telah dilalui negara lain, bukan satu keniscayaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.






















![[HOAKS] Bendera GAM Berkibar Setelah Prabowo Menang Sengketa Pilpres di MK](https://asset.kompas.com/crops/k61Jxb0rnf1AjoftSCvVz9fGnS4=/0x0:750x500/170x113/data/photo/2021/12/09/61b22443e24a9.jpg)



![[HOAKS] MK Telah Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran](https://asset.kompas.com/crops/5JoenEELPq1mOdHChup49ItUh5o=/0x17:1477x1001/170x113/data/photo/2019/08/06/5d48ef7d72495.jpg)