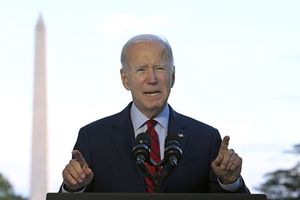Oleh: SUKARDI RINAKIT
KOMPAS.com - SAYA ikut gembira menyaksikan dari layar televisi pelantikan Alex Noerdin dan Ishak Mekki menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (7/11). Dalam penelitian indeks pembangunan yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate tahun lalu, ”Bumi Sriwijaya” itu menduduki posisi kedua di bawah Jawa Timur yang bertengger di puncak. Gerak pembangunan itu idealnya memang dijaga oleh nakhoda yang sama.
Kegembiraan yang sama juga saya rasakan ketika menghadiri pesta pernikahan putri Sultan Hamengku Buwono X. Ketika malam hari berbaur di pesta rakyat yang diselenggarakan warga Yogyakarta, sahabat saya Widihasto Wasana Putra yang menjadi koordinator acara mengatakan, ”Pesta rakyat ini wujud nyata bahwa keraton tidak berpisah dengan rakyat. Kegembiraan keraton juga kegembiraan rakyat, dan sebaliknya.” Dia benar. Penulis yang orang Jawa Timur saja juga ikut bahagia saat itu.
Dua peristiwa tersebut membenarkan bekerjanya teori modal sosial di ranah politik. Terlepas dari kontroversi yang mungkin ada, seorang pemimpin yang bekerja dan kaya jaringan sosial, apalagi menjadi pengayom seperti Sultan, tentu akan dicintai rakyatnya. Apabila ada pihak-pihak yang dirasa mengganggu, seperti kasus keistimewaan Yogyakarta dulu, pembelaan masyarakat akan mengalir deras tak terbendung.
Demikian juga dengan fenomena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Pengamatan pada media sosial ataupun kondisi lapangan menunjukkan, siapa pun yang mencoba mengkritik Jokowi, apalagi secara tidak fair dan diduga mempunyai agenda politik terselubung, dia pasti akan diserbu balik oleh kelompok masyarakat yang menghormati dan mencatat langkah- langkah kebijakan yang dia ambil selama ini.
Dalam perspektif budaya politik, fenomena itu menunjukkan bahwa kinerja dan performa seorang pemimpin pada dasarnya merupakan transformasi dari sumber-sumber kekuasaan yang oleh Ben Anderson (1990) disebut konkret. Dengan demikian, kinerja yang baik, misalnya, boleh disebut sebagai padanan dari wahyu kekuasaan (pulung), keris, dan tombak yang menjadi sumber dan legitimasi kekuasaan dalam bentuknya yang lain.
Dengan istilah lain, kinerja seorang pemimpin itu seperti ”opor bebek”. Ia tidak perlu ditambah minyak karena bisa mengeluarkan minyak sendiri ketika direbus sehingga rasa opor jadi enak (opor bebek mentas saka awake dhewek). Inilah narasi dalam bentuk mitos yang disematkan masyarakat kepada tokoh yang mereka proyeksikan dapat menjadi sandaran keluh kesah rakyat. Pemimpin seperti itu, meminjam Slank, ”enggak ada matinya”. Ia bukan seperti para politisi yang miskin virtue (kebajikan), yang berjanji soal keadilan, tetapi di bawah panggung mereka bercumbu dengan setan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berpendidikan rendah, yang kultur dasarnya adalah oral, kekuatan narasi sulit dipatahkan oleh strategi politik konvensional, apalagi sekadar memproduksi wacana konfrontatif. Narasi itu, sesuai hasil survei dari beberapa lembaga independen, suka atau tidak, kini mengurapi dan menyelimuti Jokowi.
Dalam situasi demikian, seorang calon presiden yang populer dan memiliki akseptabilitas tinggi, misalnya Prabowo Subianto, apabila langkah politiknya tidak terukur seperti terlalu aktif, jika tidak boleh disebut agresif, secara hipotesis akan berdampak terhadap perolehan suara Gerindra. Suara partai itu bisa tidak sebesar yang mereka perkirakan.
Hal itu disebabkan pemilih khawatir calon tersebut akan menjadi pesaing kuat dari tokoh yang mereka dukung dan sudah menjadi bagian dari narasi publik, misalnya Jokowi. Masyarakat akhirnya justru memutuskan tidak memilih partai yang mengusung calon presiden yang manuvernya terlalu aktif itu. Secara alamiah, masyarakat membangun mekanisme seleksi untuk melindungi ”jago” yang sudah mereka elus-elus.
Sebaliknya, apabila partai politik tempat tokoh yang diselimuti narasi itu tidak mencalonkannya, seluruh jaringan pendukung secara sentimental akan melakukan eksodus. Mereka akan lompat pagar, memberikan dukungan, dan bekerja untuk tokoh yang namanya berada di urutan kedua dalam popularitas dan elektabilitas. Selain itu, apatisme publik juga akan meningkat sehingga angka golput otomatis akan tinggi.
Menguatnya preferensi politik masyarakat pada kinerja dan pesona figur tersebut secara nyata telah menggeser daya magis ideologi seperti yang berlaku di era Orde Lama dan keterikatan pada partai politik di era Orde Baru. Ini menunjukkan praktik politik di Tanah Air sudah menyatu dengan budaya pop.
Sisi negatif dari perkembangan tersebut adalah pragmatisme politik, khususnya pencitraan dan politik uang menebar seiring dengan desain pemilihan langsung. Positifnya, peluang munculnya tokoh-tokoh yang berakar dari rakyat terbuka lebar.
Di luar itu semua, hal yang perlu diwaspadai seiring dengan menguatnya preferensi politik pesona figur adalah meningkatnya fanatisme pendukung. Apabila seorang tokoh kalah dalam kontestasi politik dan mencurigai ada manipulasi suara, ia bisa menggerakkan massa fanatiknya. Tentu, tokoh seperti itu secara politik mudah mati. Ia tidak berkarakter “opor bebek”.
SUKARDI RINAKIT , Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation
























![[KLARIFIKASI] Tidak Benar Minyak Goreng](https://asset.kompas.com/crops/rA48DJ0A2Ju8NOHjipr-gpn2eo0=/0x0:1563x1042/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9cb3fac5ac.png)