
SEBAGAI seorang perwira militer aktif, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Udara, netralitas dalam politik memang harga mutlak.
Namun, meskipun tidak memiliki hak pilih, perjalanan menjadi ajudan seorang menteri banyak membuka mata dan pikiran penulis tentang berbagai realita kehidupan bernegara, termasuk tentang bagaimana pola pikir para politisi di negara kita.
Penulis mendapatkan kesempatan selama beberapa tahun mengamati secara empiris interaksi antarelite politik di lingkungan pemerintahan, serta di lingkungan partai politik. Dan kesimpulannya memang, miris.
Mengapa demikian? Politik di negara demokrasi baru seperti Indonesia bukanlah sesuatu yang penuh dengan idealisme, tetapi justru penuh dengan pragmatisme dan dicengkram oleh plutokrasi.
Di sini, penulis tidak bermaksud untuk menyudutkan satu pihak tertentu, tetapi hanya menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dalam perpolitikan negara kita.
Film dokumenter “Dirty Vote” yang baru saja dirilis pada hari tenang sebelum hari pencoblosan dimulai sedikit menggelitik saya untuk menulis artikel ini.
Pertama, mengapa pragmatis? Sekilas memang berbagai aktor politik ataupun lembaga-lembaga yang menaunginya, dalam hal ini partai politik, memang mewakili suatu identitas ataupun ideologi tertentu.
Ada yang berhaluan ideologi kanan keagamaan, tengah atau moderat, atapun kiri yang lebih progresif.
Namun, semua ideologi dan paham yang dianut partai-partai tersebut, yang seperti menjadi representasi bagi sebagian atau sekelompok masyarakat tertentu, kini menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada suatu fase dalam kontestasi elektoral, yaitu: pembentukan koalisi.
Adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mengharuskan suatu partai atau gabungannya hanya dapat mencalonkan capres dan cawapres jika melewati perolehan kursi paling sedikit 20 persen di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional seperti memaksa seluruh partai politik melakukan hubungan yang sifatnya “transaksional”.
Ada yang bergabung dengan partai ini, partai itu, dan ada pula yang percaya diri mencalonkan presiden dari partainya sendiri tanpa berusaha membangun sebuah koalisi.
Situasi ini menciptakan kesan bahwa lembaga maupun aktor politik yang memiliki idealisme tertentu, tetapi kurang suara pada pemilu sebelumnya, terpaksa harus menjalani serangkaian lobi-lobi guna memuluskan agenda politiknya.
Apa agendanya? Tentu saja posisi jabatan. Ada yang ingin jadi mendapatkan posisi ketua di lembaga legislatif, menteri, ataupun kekuasaan tertinggi di eksekutif, yakni presiden dan wakil presiden.
Dapat dikatakan, lobi-lobi internal antarpartai ataupun perseorangan semacam inilah yang sebenarnya luput dari perhatian masyarakat dan sangat berbahaya.
Mengapa? Karena pembicaraan ini tidak dilaksanakan secara terbuka dan hanya melibatkan pertemuan tertutup antar elite. Akibatnya, kepentingan rakyat dan masyarakat luas luput dalam pembahasan pembentukan koalisi.
Seringkali, yang dibicarakan dalam pertemuan dan lobi-lobi ini hanya sekadar masalah angka: elektabilitas, hasil survei, jumlah suara tiap dapil, kekuatan relawan di daerah dan sebagainya.
Apakah ada hal-hal yang sifatnya kepentingan publik secara luas dibicarakan dalam forum transaksional semacam ini? Sayang seribu sayang, sejak 2019 dan kini 2024, penulis melihat hal tersebut sangat langka untuk didengar.
Suara masyarakat seolah hanya diukur dari segi angka persentase keterpilihan daripada substansi yang harusnya menjadi pokok persoalan masyarakat yang diwakilinya.
Keberadaan konsultan politik yang menaungi berbagai survei, namun juga ikut membantu pemenangan suatu koalisi tertentu, seolah semakin mengalihkan fokus bagi apa yang idealnya dilakukan bagi seorang wakil rakyat untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini tentunya jauh dari kondisi yang “ideal” bagi negara demokrasi.
Parahnya, idealisme kadang hanya menjadi komoditas politik, bukan cita-cita luhur yang ingin dicapai.
Sebagai contoh, partai-partai Islam yang seharusnya mewakili suara-suara masyarakat yang diwakilinya, justru memanfaatkan doktrin dogmatis keagamaan demi mendulang suara dan meraih kekuasaan.
Doktrin-doktrin keagamaan yang tadinya dianggap sebagai nilai-nilai luhur di masyarakat, justru dimanfaatkan oleh para politisi sehingga turun derajatnya menjadi doktrin dogmatis yang sarat akan kepentingan.
Berbagai partai berhaluan non-agama yang juga turut memanfaatkan situasi seperti ini turut berkampanye di area komunitas keagamaan seperti pesantren, padepokan, ataupun madrasah demi memanfaatkan “doktrin” keagamaan yang diyakini oleh para masyarakat di sekitarnya.
Akibatnya, suara komunitas-komunitas tersebut akhirnya terpecah secara politik, dan menimbulkan fragmentasi cara pandang antarinternal komunitas keagamaan.
Kedua, mengapa dicengkram plutokrasi? Sebagai informasi, plutokrasi berarti kekuasaan yang digenggam oleh sekelompok orang yang memiliki kekayaan luar biasa.
Hampir sebagian besar politisi kita pasti memiliki latar belakang bisnis. Sehingga, politik menjadi suatu ranah yang accessible bagi pebisnis karena mahalnya biaya yang diperlukan untuk terjun ke dunia politik.
Dalam menggerakan mesin partai dan pengerahan massa serta atribut saat kampanye, uang seakan-akan menjadi modal politik yang paling diperlukan dan merupakan bentuk power yang paling dominan dibanding citra lembaga ataupun individu.
Maksud penulis, siapa orang di dunia saat ini yang tidak butuh uang?
Money politics memang ada dan nyata di mana-mana. Namun layaknya elite yang menghalalkan segala cara, masyarakat kita pun tidak benar-benar mengkritik hal ini di dunia nyata. Tidak peduli halal atau haram, asal cuan, terima saja tidak masalah.
Istilah “serangan fajar” ataupun bagi-bagi hadiah menjadi hal yang lazim untuk diterima dan bukan hal yang patut untuk dikritisi.
Budaya demokrasi yang cenderung feodal ini memang menargetkan kaum-kaum yang memang terbelakang secara ekonomi dan pendidikan, sehingga membuat si pemberi terasa sebagai seorang malaikat.
Tidak melulu berbentuk uang, ada pula yang mengandalkan bantuan sosial berupa sembako, yang kadang juga menggunakan program dari pemerintah (bukan dari kantong pribadi), sebagai alat untuk mendongkrak suara di daerah pemilihan.
Masyarakat pun banyak yang menerima “bantuan” semacam ini tanpa mau tahu dari mana datangnya sumber dana pengadaannya. Kembali lagi, terima saja dulu.
Pengamatan penulis di lapangan akan fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat kita memang tipe orang yang sangat pragmatis, tidak hanya elite, namun juga warga dengan kemampuan ekonomi menengah kebawahnya.
Plutokrasi akhirnya menempatkan pebisnis dengan kekuatan kapital yang sangat dominan berada pada posisi struktur lembaga politik tertentu tanpa memandang ideologi lembaga ataupun latar belakang ideologis sang politisi tersebut.
Misalnya, seseorang dengan modal besar, yang semula tidak berpenampilan agamis, tiba-tiba menjadi petinggi di partai berideologi kanan agamis.
Hal ini memang sah-sah saja, tapi semakin mengonfirmasi dominannya tantangan terbesar dalam menjalankan roda kepartaian: ongkos kampanye.
Semua yang memiliki ideologi tertentu, pada akhirnya akan dihadapkan pada situasi pragmatis (termasuk masalah biaya operasional partai), demi meraih tujuan di lingkungan kekuasaan.
Maka tidak heran, segala kondisi keterpaksaan berperilaku pragmatis, serta banyaknya modal yang dikeluarkan menghasilkan motivasi politik jangka pendek yang intinya adalah: “yang penting menang”.
Apapun ideologi politiknya, penulis menemukan bahwa “menang” adalah inti tujuannya.
Demokrasi turun derajatnya, di mana tidak lagi dipandang sebagai jembatan demi mendengar aspirasi semua orang, namun lebih dominan kepada jembatan bagi satu individu atau kelompok demi meraih cita-cita kekuasaan.
Hal ini mempertegaskan indeks demokrasi Indonesia yang pada tahun 2022 lalu digolongkan oleh The Economist Group sebagai flawed democracy (demokrasi cacat).
Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara adil dan bebas, namun memiliki masalah pada aspek-aspek kelembagaan maupun budaya demokrasinya.
Apabila budaya demokrasi yang terlalu pragmatis seperti ini masih dipelihara oleh para politisi dan masyarakat kita, tentunya akan menggerus cita-cita ideologis bangsa Indonesia yang sudah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.












































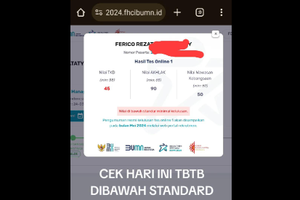





![[POPULER JABODETABEK] Yudha Arfandi Benamkan Dante Saat Berenang dengan Sang Putri | Dalih Yudha Benamkan Dante 12 Kali](https://asset.kompas.com/crops/rBSdJwymYPls-J4DkoK4pfkMyII=/0x0:0x0/95x95/data/photo/2024/02/12/65c9f0eab0d37.jpg)







