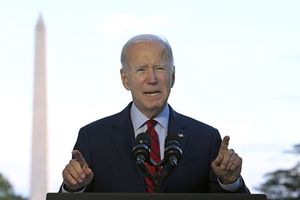Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan
BI Purwantari
Meskipun landasan kebangsaan ini telah disetujui bersama oleh anak bangsa, sejarah mencatat, ribuan orang telah menjadi korban dari perjuangan mewujudkan hak-hak asasi, termasuk kebebasan beragama di negeri ini. Pada masa Orde Baru, di mana kekuatan politik negara sangat kuat, cara-cara represif sering digunakan untuk membungkam suara kelompok-kelompok agama dan penghayat kepercayaan yang dinilai mengganggu stabilitas.
Pasca-Orde Baru, berbagai produk hukum lahir sebagai hasil dari kontestasi etnopolitik kelompok-kelompok masyarakat. Selain konstitusi, lahir pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik. Meski demikian, efektivitas praktis dari perundangan itu ternyata belum mampu memperbaiki keadaan. Landasan kebinekaan tetap relatif rapuh di hadapan sikap agresivitas kelompok radikal.
Dengan sejumlah payung hukum dan ruang kebebasan yang lebih longgar, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan belum membaik signifikan. Sebaliknya, sejumlah hak kelompok minoritas dilanggar dan tak terlindungi.
Lebih dari separuh responden (54,7 persen) menilai, hak warga minoritas agama dalam beribadah dan mendirikan tempat ibadah belum terlindungi. Sementara 39,1 persen responden menilai sebaliknya. Penilaian yang sedikit lebih baik disuarakan publik terhadap kebebasan masyarakat adat dan warga Tionghoa dalam kebebasan berekspresi dan menjalankan adat kebiasaan.
Pola jawaban responden menunjukkan bahwa praktik pemberian kebebasan beribadah kepada kelompok-kelompok minoritas (termasuk Ahmadiyah) dijawab dengan hati-hati. Semakin berjarak dengan aspek doktrinal agama, semakin besar proporsi responden dalam memberikan hak kebebasan kepada kelompok minoritas. Artinya, ada nuansa jawaban yang tersirat bahwa kebebasan dan perlindungan kepada minoritas adalah sebuah keniscayaan.
Dalam laporan tahunannya, Setara Institute merekam terjadinya 299 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama pada 2011. Peristiwa serupa terus terjadi pada tahun berikutnya. Sejak Januari hingga Juni 2012, menurut lembaga ini, telah terjadi 129 peristiwa pelanggaran dan 179 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun pelanggaran kebebasan beragama menyentuh semua kelompok agama, termasuk kelompok mayoritas, kelompok minoritas tetap yang paling kerap dilanggar hak-haknya.
Menurut Setara Institute, pelanggaran ini dilakukan, baik oleh kelompok-kelompok di masyarakat maupun institusi negara. Institusi negara yang paling banyak melanggar adalah pemerintah daerah (36 persen) dengan berbagai perangkatnya, sementara kepolisian sebanyak 33 persen.
Bagi publik jajak pendapat ini, sejumlah kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap menjadi pemicu dilanggarnya hak-hak kelompok minoritas. Secara tegas, lebih dari separuh responden (54,4 persen) menilai, keputusan Menteri Agama terhadap Ahmadiyah melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Jika peristiwa-peristiwa itu ditanyakan dalam konteks peran negara, sebanyak 74,1 persen responden bahkan menilai hal itu ”pembiaran dan memelihara” konflik.
Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis agama yang terjadi di masyarakat tidak berdimensi tunggal. Di luar soal doktrin keagamaan, lemahnya sikap pemerintah terhadap aksi kekerasan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan pelanggaran. Tidak jarang pula dijumpai kecenderungan keberpihakan aparat terhadap pandangan kelompok mayoritas sehingga mengorbankan kelompok minoritas.
Prof Musdah Mulia menyebutkan dalam buku Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi bahwa iklim kebebasan beragama di Indonesia sulit diwujudkan karena krisis peranan dan krisis kesadaran. Krisis peranan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Krisis dimaksud adalah tanggung jawab untuk berperan aktif merealisasikan UU yang ada dan dirasa cukup untuk menjamin kebebasan beragama. Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik pemerintah maupun masyarakatnya
”Pemerintah mesti menyadari peran obyektif mereka untuk mengatasi masalah kebebasan beragama, bukan malah menjadi kekuatan membelenggu kebebasan tersebut,” tulisnya.
Di beberapa wilayah, potensi pelanggaran kebebasan beragama bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan. Hal ini dimungkinkan sepanjang para pemimpinnya, yang merupakan representasi dari negara, bersedia menjamin dan melindungi hak sipil dan politik yang khusus ini.
Beberapa contoh bisa disebutkan di sini. Konflik yang sempat mencuat di Solo, Jawa Tengah, pada September 2012 antara warga Solo dan kelompok radikal tertentu bisa diselesaikan dan tidak meluas. Atau potensi konflik yang muncul di wilayah Yogyakarta terkait pembangunan tempat ziarah kelompok agama tertentu pada Maret 2011.
Pada kedua peristiwa tersebut, peran pemimpin sangat krusial. Keduanya berhasil menengahi konflik dan mengajak warga untuk tetap menghormati kebebasan beragama kelompok lainnya sambil bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan. Hasilnya, konflik tidak meluas dan hak untuk bebas beribadah tetap terlindungi.
Peran negara dengan demikian signifikan. Bukan hanya karena institusi inilah yang seharusnya menjadi jembatan negosiasi terus-menerus antarkelompok yang berpotensi konflik, melainkan juga karena sikap toleran yang muncul di masyarakat tidak bisa bertahan jika negara tidak bisa menjaga keberlanjutannya.
Seperti diungkap oleh sebagian besar publik survei ini bahwa landasan toleransi telah terbangun di masyarakat. Tujuh dari 10 responden secara lugas menyatakan bersedia memilih pemimpin yang berbeda agama dengan dirinya. Demikian pula halnya dengan kesediaan memberikan izin pendirian rumah ibadah bagi kelompok agama yang berbeda. Sebanyak 73,8 persen responden tidak ragu menyetujuinya.
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 telah membuktikan perihal kehendak kebinekaan yang masih menjadi arus utama di masyarakat. Di tengah kuatnya gelombang kampanye berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, para pemilih tetap bergeming untuk memilihnya.
Sikap toleran dan pro-kebinekaan seperti ini merupakan modal untuk kembali menguatkan peran negara dalam merangkum kebinekaan. (Litbang Kompas)