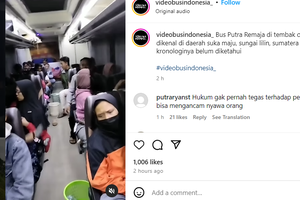Pidato SBY Mengecewakan
Tuturnya terjaga, irama dimainkan dengan baik, turun-naik, mengeras dan melembut, disertai beberapa sentakan staccato, juga klimaks-klimaks yang menciptakan impresi seorang orator yang kini kian langka.
Mungkin itulah pidato terbaik yang pernah saya lihat dan apresiasi dari seseorang yang memperlihatkan kualitas kenegarawanan, lebih kuat ketimbang ia memegang jabatan sebelumnya. Penilaian itu tak hanya didasarkan pada kelugasan dan kecakapan mengartikulasikan kata dan ide, tetapi lebih utama pada ide yang ada di dalamnya. Bukan hanya ia memberi komentar kritis dan solusi yang menarik bagi berbagai persoalan mutakhir bangsa ini, melainkan juga teknokrat unggul tersebut menyentuh persoalan berdimensi sosial, etis, dan kebudayaan, hingga pada masalah perilaku masyarakat yang menyimpang belakangan ini.
Apa yang paling menarik adalah ketika ia melakukan koreksi yang kritis justru pada kekuatan ilmu atau sains, intelektualisme, rasionalisme, dan demokrasi di mana ia menjadi eksponen utamanya. Di sini kita mendapatkan seorang figur yang telah berhasil melampaui (kapasitas dan kepentingan) dirinya sendiri dan berdiam dalam dunia ide yang memayungi kepentingan semua golongan dan kelompok-kelompok sektarian lainnya.
Setelah wafatnya Soeharto dan Gus Dur—dua presiden sebelumnya, yang dengan segala kekurangannya kita terima dengan baik kualitasnya sebagai negarawan—sosok BJ Habibie seperti mengisi kerisauan kita tentang absennya manusia Indonesia dalam kualitas puncak itu. Kualitas yang sungguh-sungguh kita harapkan dapat ditemukan pada presiden kita hari ini, Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, tampaknya, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi. Apa yang diperlihatkan oleh SBY dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPD-DPR, 16 Agustus 2011, pagi, menunjukkan bagaimana sebagai kepala negara ia masih tak dapat membagi diri, peran, dan tugasnya sebagai eksekutif yang memimpin lembaga pemerintahan dengan posisinya sebagai pemimpin yang meng-”atas”-i kepentingan sempit golongan, agama, suku, bahkan seluruh lembaga negara yang ada.
Sebagai kepala negara selaiknya ia menciptakan ruang abstrak terluas sebagai universum, dengan semua elemen atau pemangku kepentingan hanya jadi himpunan bagian. Ia adalah representasi bangsa, entitas tempat negara dan kemudian pemerintahan dilahirkan.
Yang kita dengar dalam pidato SBY di sidang bersama itu hampir seluruhnya menggambarkan hasil kerja dan kesuksesan pemerintahannya, program, dan cara-cara seorang eksekutif memberi solusi bagi persoalan-persoalan pragmatis rakyatnya. Persoalan-persoalan yang ternyata harus diakui didominasi perhitungan-perhitungan ekonomis, plus beberapa perhitungan politik dan hukum, serta sedikit tersinggung soal pendidikan, daerah, dan diplomasi luar negeri.
Tentu ini menciptakan kerancuan dengan pidato pengantar RAPBN sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai kepala pemerintahan pada Sidang Paripurna DPR, siang harinya. Kerancuan itu juga terlihat dengan setidaknya enam kali ia mengucapkan kata ”pemerintah(an)” dalam pidato kenegaraannya.
Tampaknya SBY sungguh hendak memanfaatkan semua mimbar, terlebih mimbar kenegaraan sepenting sidang bersama, untuk mengeksplanasi keberhasilan kerja eksekutif atau pemerintahannya. Sebuah kehendak yang akhirnya membuat ia selalu gagal melihat persoalan inti dari berbagai problem kebangsaan yang melanda kita belakangan ini.
Mungkin sebagaimana banyak pemimpin negeri-negeri lain, SBY pun melihat problematik kekinian itu berakar dan dapat diselesaikan ketika kesejahteraan atau dimensi ekonomi dapat dituntaskan dengan baik, memenuhi sebagian harapan publik. Namun, pendekatan pragmatis dan materialistis tak dapat menghindari siapa pun—bangsa dan pemimpinannya—dari persoalan-persoalan sosial, kultural, dan spiritual yang kian mengimpit belakangan ini.
Berbagai peristiwa di banyak belahan dunia, juga di Tanah Air, menunjukkan bagaimana penyelesaian ekonomi tak selalu jadi solusi paling jitu dari berbagai persoalan bangsa. Cara kita hidup, bersosialisasi, dan berinterelasi, cara kita mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan, beragama, berkesenian/berbudaya, atau berkelompok/berorganisasi sampai menjalankan bisnis dan berpolitik adalah hal-hal yang jadi titik kegelisahan masyarakat akhir-akhir ini. Hal-hal itu justru ternyata luput dari perhatian sang kepala negara.
Kita tak berhasil menemukan pikiran-pikiran dalam pidato kepala negara kemarin, yang mengidentifikasi di mana substansi dan esensi dari semua masalah itu. Kita gagal memperoleh masukan untuk hati dan pikiran kita, pandangan-pandangan visioner kepala negara, juga solusi-solusi etis, moral, dan kultural di mana soal-soal di atas dapat dipecahkan. Krisis kebangsaan, dalam dimensinya yang tidak material, telah ternafikan secara sengaja dalam cara (kepala) negara menunaikan tugasnya.
Akibatnya, untuk hampir satu dekade masa pemerintahan SBY, kita pun tak kunjung mendapatkan pegangan yang kuat untuk mengatasi berbagai persoalan akut sehari-hari. Persoalan yang membuat seseorang jadi kalap, frustrasi, bahkan bunuh diri hanya karena tak mampu menanggung beban hidup keseharian yang diakibatkan oleh kompetisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak adil; oleh sistem yang pada nalurinya memang sudah berpihak pada yang ber-”ada”.
Pegangan itu selayaknya diketahui oleh kepala negara. Sayang, sungguh sayang, kembali kita tertunduk penuh sesal dan malu karena negeri sebesar ini, potensi sumber daya sehebat ini, tak kunjung juga melahirkan pemimpin semacam itu. Pemimpin dengan keberanian untuk berpikir besar, berbuat besar, dan mengambil risiko besar. Kita menjadi bangsa yang medioker, yang hidup dengan safety belt ketat melilit tubuh. Seperti orang kaya yang tidak berani membuka pagar dan halamannya, menutup diri dengan tembok tinggi dan canggihnya sistem sekuriti.
Inilah dasar kekecewaan ke pada sang kepala negara, figur yang selama ini ditunggu dan cari. Ternyata sistem dan mekanisme (politik) yang ada tidak mengizinkannya untuk muncul, bahkan tumbuh kecambahnya. Selalu kita terjebak dalam harapan-harapan beraroma mistis, tentang akan munculnya, ”satria piningit”, Ratu Adil, atau messiah-messiah yang sesungguhnya hanya menjadi simbol pelerai dan penghibur hati yang mengalami dislokasi dan disorientasi.
Di titik ini, umumnya sebuah tulisan akan mengakhiri dengan sebuah harapan, keyakinan messianistik atau ancaman yang bersifat ekstrem, masif, atau radikal. Tetapi, tidak tulisan ini. Kita harus mengakhirinya dengan sebuah awal. Awal untuk mendapatkan pemimpin bangsa itu. Siapa pun dia, kita mesti siap menyambutnya. Betapapun mungkin sistem menolaknya. Kita bisa? Bisa!