
Pancasila Membutuhkan Keteladanan
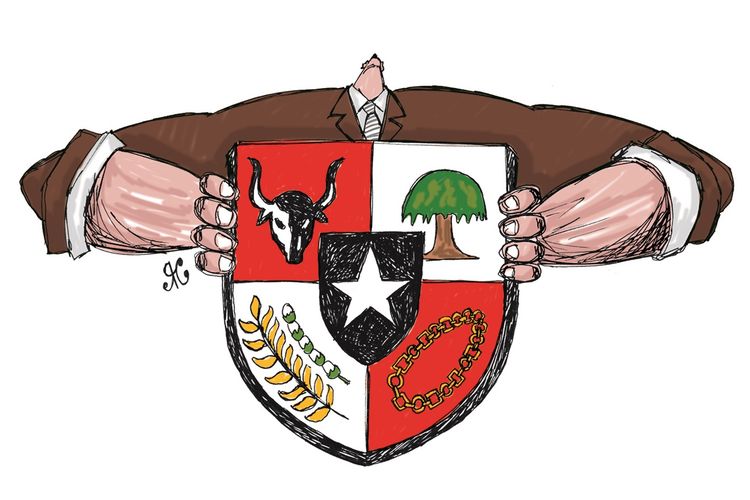
SEMENJAK tahun 2016, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Pancasila.
Penetapan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016.
Hal ini didasarkan pada pidato Bung Karno ketika menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI tentang filosofische grondslag yang kemudian diberi nama Pancasila.
Persoalan hari lahirnya Pancasila sering menjadi perdebatan dengan argumen masing-masing. Namun persoalan yang lebih mendasar sebenarnya bukan hari lahir, tetapi pada bagaimana mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, setiap rezim selalu menyatakan akan melaksanakan Pancasila dalam praktik bernegara. Namun, faktanya mereka juga melakukan penyimpangan terhadap Pancasila.
Rezim Orde Lama yang dipimpin oleh penggali Pancasila juga telah menyimpangkannya. Begitu juga rejim Orde Baru yang lahir dengan semangat melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, juga melakukan penyelewengan terhadap Pancasila.
Di era reformasi juga masih banyak praktik penyelenggaraan negara yang belum sesuai dan bahkan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
Apakah Pancasila begitu rumit dan sulit untuk diamalkan? Atau Pancasila hanyalah othopia yang tidak bisa dipraktikkan? Atau kita yang kurang serius dan sepenuh hati untuk mengamalkannya? Pertanyaan ini perlu kita renungkan.
Jika kita mengacu kepada pernyataan Soekarno bahwa Pancasila digali dari adat dan budaya masyarakat yang hidup di bumi nusantara, maka seharunya tidak sulit untuk mengamalkannya.
Nenek moyang kita telah mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Religiusitas sebagai perwujudan dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka praktikkan bukan hanya dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap jujur dan “nrimo” atas hasil yang telah mereka usahakan merupakan bentuk nyata dari pengamalan atas apa yang mereka yakini bahwa Allah Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana.
Meskipun dalam kesepian dan kesendirian, kesadaran religiusitas menjadi bintang pemandu, Life Star (meminjam istilah Dardji Darmodihadjo) dalam setiap langkahnya.
Mereka memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh moral dan agama.
Rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama sebagai manifestasi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian dari “harga diri” yang terus dijaga dan dipelihara.
Rasa malu merupakan ciri keberadaban seseorang. Dengan rasa malu tersebut, mereka mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela (melanggar norma moral, sosial dan agama).
Kegotongroyongan sebagai esensi sila ketiga telah menjadi budaya masyarakat. Nenek moyang kita bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa membedakan suku, agama maupun golongan.

























































